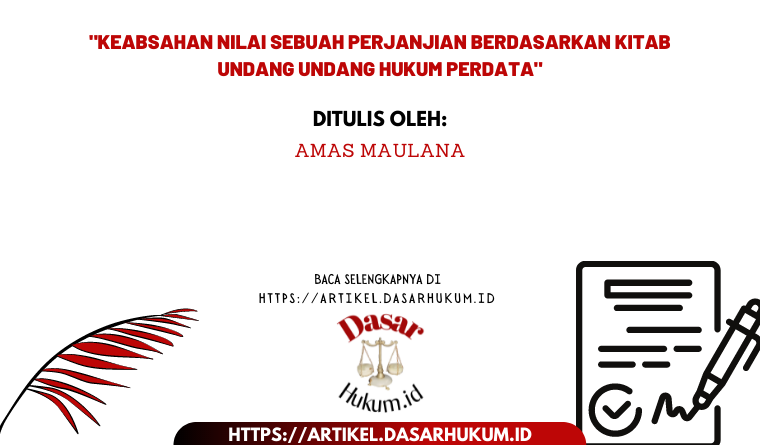Sekapur Sirih
Ungkapan Socrates sekitar 2500 (dua ribu lima ratus) tahun yang lalu, yaitu: “The beginning of wisdom is the definition of terms (awal mula dari kebijaksanaan adalah definisi dari suatu istilah)” (Hollingsworth, 2015) rasanya cukup sulit untuk dikontekskan dengan hukum yang notabene hingga sekarang masih belum adanya keseragaman dari setiap orang di dunia. Bahkan, para ahli hukum (jurist) di dunia rasanya masih memiliki perspektif yang berbeda-beda terkait dengan definisi dari hukum itu sendiri (Apeldoorn, 2019). Adanya multi perspektif terkait dengan definisi hukum ini, sejatinya koheren dengan pendapat I. Kisch yang menyampaikan, bahwa: “doordat het recht onwaarneerbaar is onstaat een moeilijkheid bij het vinden van een algemen bevredigende definitie (sebagai akibat hukum tidak dapat ditangkap oleh pancaindra, maka merupakan hal yang sulit untuk membuat suatu definisi tentang hukum yang dapat memuaskan orang pada umumnya) (Ali, 2009).” Walaupun, masih belum ada kesepahaman mengenai definisi hukum, namun ada satu hal terkait hukum yang bersifat endoxon (Boukala, 2016), yaitu hukum dipercaya sebagai solusi paling tepat dalam menyelesaikan suatu sengketa.
“Cum adsunt testimonia rerum, quid opus est verbis? (Ketika bukti dari suatu fakta sudah ada, maka apa guna kata-kata?)”(Garner, 2014). Adapun, salah satu bukti, bahwa hukum dipercaya sebagai solusi dalam menyelesaikan suatu sengketa adalah, masih tingginya jumlah perkara yang masuk di pengadilan. Misal di Indonesia yang pada tahun 2020 saja terdapat 20.761 (dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh satu) perkara yang masuk (Tim Pokja Laporan Tahunan MARI, 2020). Jumlah yang sangat besar tersebut sejatinyaa menunjukan, bahwa di Indonesia, masih banyak masyrakat yang mempercayai institusi pengadilan dalam menyelesaikan sengketa daripada melakukan main hakim sendiri (eigenrechting) (Putra et al., 2016).
Dari tingginya perkara yang masuk tersebut, ternyata hampir sebagian besar para pihak yang berperkara ini memberikan surat kuasa (biasanya surat kuasa khusus/bijzondere schriftelijke machtiging) kepada seorang advokat/penasehat hukum. Walaupun, memakai kuasa hukum, yaitu secara umum bukanlah kewajiban, karena tidak dianutnya sistem verplichte procureur steling (terdapat beberapa perkara yang wajib menggunakan kuasa hukum, misal dalam perkara pidana dengan ancaman pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih seperti yang diatur di dalam Pasal 56 ayat [1] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) (Suslianto, 2019), namun para pihak merasa lebih optimis ketika diwakili dan/atau didampingi oleh seorang advokat yang seyogyanya lebih menguasai hukum daripada dirinya.
Dalam menggunakan advokat, tentunya hal pertama yang perlu dilakukan oleh para pihak yang bersengketa tersebut adalah memberikan kuasa kepada advokat tersebut. Tanpa adanya kuasa ini, advokat tersebut tidak bisa mewakili dan/atau mendampingi pihak tersebut. Dengan dasar tersebut, maka bisa dibilang kuasa ini merupakan prima facie dalam menggunakan seorang advokat (Hartanto, 2019).
Kedudukan kuasa yang sangat penting dalam menggunakan seorang advokat ini, memang sangat penting, namun ternyata masih sering dianggap remeh. Bahkan, pembuatan kuasa ini sering dilakukan secara sembarang. Terkait dengan syarat-syarat yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan sering tidak diperhatikan. Padahal, surat kuasa khusus yang demikian ini sejatinya memiliki akibat hukum, seperti surat gugatan tidak sah, pemeriksaan tidak sah, bahkan tidak menutup kemungkinan pihak yang mewakili tersebut diminta untuk turut bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang telah dilakukannya (Gumilang et al., 2019).
Adapun salah satu permasalahan penerapan kuasa yang sering ditemukan dalam praktik peradilan yang notabene muncul karena kurangnya perhatian pemberi dan/atau penerima kuasa adalah terkait dengan surat kuasa khusus yang dibuat di luar negeri dalam perkara perdata. Banyak pihak yang mengira, bahwapembuatan kuasa di luar negeri memiliki syarat yang sama dengan yang dibuat di dalam negeri (domestik) dan kemudian cukup di legalisasi oleh KBRI setempat atau Konsulat Jendral setempat, padahal terdapat syarat lain yang diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 (selanjutnya disebut SEMA 7/2012) rumusan kamar perdata, sub kamar perdata umum bagian I huruf f, yaitu perlunya dibubuhi pemateraian kemudian di kantor Pos (nazegelen).
Adanya syarat nazegelen yang jarang diketahui oleh orang-orang ini membuat para advokat (para penerima kuasa), umumnya setelah memperoleh kuasa yang dilegalisasi oleh perwakilan RI yaitu Kedutaan atau Konsulat Jenderal di tempat surat kuasa khusus tersebut di buat kemudian mendaftarkan kuasa tersebut ke pengadilan negeri setempat. Tidak dilakukannya nazegelen yang notabene merupakan amanat dari SEMA 7/2012 tentunya menimbulkan pertanyaan mendasar terkait dengan apaka akibat hukum dari tidak dilakukannya hal tersebut. Apakah tidak yaitu apakah ada syarat lain pada surat kuasa khusus yang dibuat di luar negeri? Dengan dasar tersebut, maka perlu dianalisis lebih lanjut terkait dengan syarat keabasahan surat kuasa khusus yang dibuat di luar negeri
Keabsahan Surat Kuasa Khusus Secara Umum
Di dalam Pasal 1792 Burgerlijk Wetboek (selanjjutnya disebut BW), diatur definisi secara umum terkait kuasa, yaitu:” Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.” Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat 2 (dua) pihak di dalam perjanjian kuasa, yaitu (Harahap, 2017):
- Pemberi Kuasa;
- Penerima Kuasa yang notabene diberi perintah atau mandat melakukan sesuatu untuk dan atas nama pemnberi kuasa.
Menurut Irene Svinarky, terdapat 4 (empat) macam kuasa, yaitu (Svinarky, 2019):
- Kuasa Umum
- Kuasa Khusus
- Kuasa Istimewa
- Kuasa Perantara
Dari 4 (empat) macam kuasa tersebut, kuasa yang digunakan sebagai landasan untuk berintdak di depan pengadilan untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak principal adalah kuasa khusus (Svinarky, 2019). Terkait kuasa khusus ini, diatur di dalam Pasal 1795 BW, yaitu: “Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa.”
Untuk memastikan, bahwa kuasa khusus tersebut, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Adapun syarat utama kuasa ini, dapat dilihat di dalam Pasal 123 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (selanjutnya disebut HIR) atau Pasal 147 ayat (1) Rechtreglement voor de Buitengewesten (selanjutnya disebut Rbg) yang berbunyi: bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat kuasa teristimewa, kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatanganinya dan dimasukkan menurut ayat pertama pasal 118 atau jika gugatan dilakukan dengan lisan menurut pasal 120, maka dalam hal terakhir ini, yang demikian itu harus disebutkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini.
Dalam konteks surat kuasa khusus, berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR, dapat dipahami bahwa syarat pokok kuasa khusus tersebut cukup berbentuk tertulis dengan tulisan “surat kuasa khusus” (Harahap, 2017).
Dalam perkembangannya, ternyata begitu sederhananya syarat yang diatur di dalam Pasal 123 ayat (1) HIR tersebut, dianggap tidak tepat. Dalam rangka menyempurnakan pengaturan terkait surat kuasa khusus ini, Mahkamah Agung berdasarkan kewenangannya yang diberikan oleh Pasal 32 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Yang Diubah Oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 membuat Surat Edaran Mahkamah Agung yang notabene merupakan petunjuk terhadap kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya (Fajarwati, 2017).
Adapun beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung yang secara khusus mengatur terkait syarat suara kuasa khusus adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober Tahun 1994 Perihal Surat Kuasa Khusus (selanjutnya disebut SEMA 6/1994). Di dalam SEMA 6/1994, diatur bahwa:
1. Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya (penebalan oleh penulis) :
a. Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebutkan antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang-piutang tertentu dan sebagainya.
b. Dalam perkara pidana harus dengan jelas menyebutkan pasal-pasal KUHP yang didakwakan kepada terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap.
2. Apabila dalam surat kuasa khusus tersebut telah disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, maka surat kuasa khusus tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan dalam kasasi, tanpa diperlukan suatu surat kuasa khusus yang baru
Dari SEMA 6/1994 tersebut, dapat dipahami bahwa syarat surat formil kuasa yang wajib ada di dalam surat kuasa khusus adalah:
- Disebutkanya secara jelas dan spesifik kegunaan surat kuasa khusus tersebut (ringkasan dan pokok objek sengketa); dan
- Disebutkan secara jelas dan spesifik peran pada tingkat pengadilan tertentu.
Terkait surat kuasa khusus ini, selain diatur di dalam SEMA 6/1994, terdapat pengaturan lain, yaitu pada Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus, terkhusus pada Bagian II Tentang Teknis Peradilan huruf F yang keberlakuannya didasarkan pada Keputusan Ketua Mahkamab Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV /2007 Tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Selanjutnya disebut Buku II Mahkamah Agung). Adapun syarat tambahan yang diatur di Buku II Mahkamah Agung tersebut (selain yang sama dengan SEMA 6/1994) adalah: “Surat Kuasa Khusus harus mencantumkan sccara jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu dengan subyek dan obyek yang tertentu pula(penebalan oleh penulis).” Dengan demikian, Adapun tambahan syarat formil berdasarkan Buku II Mahkamah Agung adalah surat kuasa khusus tersebut wajib menyebutkan secara spesifik terkait dengan identitas dan kedudukan para pihak. Contoh diperlukannya penyebutan secara spesifik terkait dengan identitas dan kedudukan para pihak ini adalah dalam Putusan Nomor 158/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel yang dalam pertimbangan hukumnya, hakim menganggap bahwa umur seseorang wajib ditulis dalam surat kuasa khusus, karena dari umur seseorang akan dapat diketahui apakah seseorang telah cakap melakukan tindakan hukum (Perbuatan Hukum).
Syarat-syarat surat kuasa khusus yang ada di dalam Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA 6/1994, dan Buku II Mahkamah Agung seiring dengan berjalannya waktu, dianggap belum cukup tepat. Hakim-hakim beranggapan, bahwa perlu terdapat syarat lain pada surat kuasa khusus yang harus ada. Adapun syarat tambahan tersebut adalah: “menyebut kompetensi realtif.” Adapun syarat ini dianggap penting, karena dengan tidak menyebutkan kompetensi relatif di dalam surat kuasa khusus, maka dianggap surat kuasa khusus tersebut tidak detail menguraikan terkait kegunaan kuasa tersebut. Hal ini misal dapat dilihat di dalam putusan Putusan Nomor 158/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel yang menyebutkan bahwa: “Menimbang, bahwa dari ketentuan yang mengatur tentang Surat Kuasa Khusus tersebut diatas, maka untuk sahnya Surat Kuasa Khusus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :…2 Menyebut kompetensi relatif…(penebalan oleh penulis);” Pentingnya penyebutan kompetensi realtif ini juga koheren dengan Pendapat M.Yahya Harahap, bahwa (Harahap, 2017): “Dengan demikian, syarat kuasa khusus yang sah ada syarat yang dideskripsi dalam pembahasan SEMA No.2 Tahun 1959, yaitu…ii menyebut kompetensi relatif…(penebalan oleh penulis)”
Berikut adalah gambar diagram alir untuk memudahkan pemahaman terkait dengan syarat keabsahan surat kuasa khusus, yaitu:
Gambar 1
Syarat Keabasahan Surat Kuasa Khusus

Keabsahan Surat Kuasa Khusus Yang Dibuat Di Luar Negeri
Dalam hukum perdata internasional terdapat doktrin the law of the forum yang berarti hukum acara yang berlaku tunduk kepada ketentuan pengadilan tempat gugatan diajukan atau diterima (Ni Made Ayu Sintya Dewi & Sukranatha, 2017). Dengan adanya doktrin tersebut, berarti segala ketentuan hukum acara yang digunakan tunduk pada locus pengadilan diajukan. Dengan demikian, pengaturan terkait surat kuasa khusus yang notaebene akan digunakan pada pengadilan di Indonesia juga menggunakan pengaturan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia.
Sesuai dengan doktrin the law of the forum yang menyebabkan pengaturan terkait surat kuasa khusus yang dibuat di luar negeri dan akan digunakan di Indonesia menggunakan hukum Indonesia, maka terkait dengan keabsahan surat kuasa khusus sejatinya juga tunduk pada pengaturan keabsahan surat kuasa di Indonesia. Hal ini berarti terkait dengan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat di luar negeri tersebut juga harus menyebutkan secara jelas dan spesifik kegunaan surat kuasa khusus tersebut (ringkasan dan pokok objek sengketa), menyebutkan secara jelas dan spesifik peran pada tingkat pengadilan tertentu yang akan digunakan, menyebutkan secara jelas kompetensi relatif terkait, dan penyebutan identitas dan kedudukan para pihak secara detail.
Selain syarat-syarat formil yang sama dengan surat kuasa khusus yang dibuat di dalam negeri, terdapat syarat-syarat lain yang harus dipenuhi, sehingga surat kuasa khusus yang dibuat di luar negeri itu sah. Adapun syarat tambahan pertama, yaitu surat kuasa khusus yang dibuat di luar negeri tersebut wajib untuk dilegalisasi oleh kantor perwakilan diplomatik Indonesia di negara tempat surat kuasa khusus dibuat(Ni Made Ayu Sintya Dewi & Sukranatha, 2017). Adapun dasar hukum dari perlunya legalisasi tersebut dapat dilihat pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Legalisasi Dokumen Pada Kementerian Luar Negeri (selanjutnya disebut Permenmlu 13/2019) yang menyebutkan, bahwa:
Pasal 4
(1) Legalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan terhadap Dokumen yang terdiri atas:
a. Dokumen yang diterbitkan di wilayah Indonesia, dan akan digunakan di luar wilayah Indonesia;
b. Dokumen yang diterbitkan di luar wilayah Indonesia atau diterbitkan oleh perwakilan negara asing yang berkedudukan di wilayah Indonesia, akan akan digunakan di Wilayah Indonesia; atau
c. Dokumen yang diterbitkan oleh perwakilan negara asing yang berkedudukan di wilayah Indonesia, dan akan digunakan di luar wilayah Indonesia.
Dengan demikian, surat kuasa khusus yang dibuat dari luar negeri yang akan digunakan untuk persidangan di Indonesia berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Permenmlu 13/2019, termasuk sebagai dokumen yang diterbitkan di luar wilayah Indonesia atau diterbitkan oleh perwakilan negara asing yang berkedudukan di wilayah Indonesia dan akan akan digunakan di Wilayah Indonesia, sehingga perlu untuk dilegalisasi
Memang, pada 5 Januari 2021, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Convention Abolishing The Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents atau Konvensi Apostille yang membuat dokumen yang dibuat dari luar negeri yang notabene memenuhi kriteria Pasal 1 Konvensi tersebut, tidak perlu dilegalisasi oleh diplomatik atau konsuler. Adapun dokumen-dokumen yang terkualifikasi di dalam Pasal 1 Konvensi Apostille yaitu:
a) documents emanating from an authority or an official connected with the courts or tribunals of the State, including those emanating from a public prosecutor, a clerk of a court or a process-server (“huissier de justice”);
b) administrative documents;
c) notarial acts;
d) official certificates which are placed on documents signed by persons in their private capacity, such as official certificates recording the registration of a document or the fact that it was in existence on a certain date and official and notarial authentications of signatures.
(Adapun terjemahan bebasnya adalah:
a) dokumen yang berasal dari suatu otoritas atau pejabat yang berkaitan dengan pengadilan atau tribunal Negara, termasuk yang berasal dari penuntut umum, panitera pengadilan atau jurusita (“huissier de justice”);
b) dokumen administratif;
c) dokumen yang dikeluarkan oleh notaris;
d) sertifikat resmi yang dilekatkan pada dokumen yang ditandatangani oleh perseorangan dalam kewenangan perdatanya, seperti sertifikat yang mencatat pendaftaran suatu dokumen atau yang mencatat masa berlaku tertentu suatu dokumen pada tanggal tertentu dan pengesahan tanda tangan oleh pejabat dan notaris.)
Dari Pasal 1 Konvensi Apostille tersebut, dapat dilihat bahwa surat kuasa khususyang dibuat di luar negeri dan akan digunakan di pengadilan negeri di Indonesia termasuk di dalam salah satu dokumen tersebut, sehingga surat kuasa khusus seyogyanya sudah tidak perlu dilegalisasi. Adapun sebagai substitusi dari legalisasi dokumen yang dibuat di luar negeri oleh diplomatik atau konsuler tersebut cukup dibuatkan suatu apostille atas dokumen itu sendiri.
Pada praktiknya, ternyata implementasi cukup apostille pada dokumen kuasa yang dibuat di luar negeri dan akan digunakan di pengadilan negeri di Indonesia termasuk di dalam salah satu dokumen tersebut, tanpa perlunya legalisasi belum selesai sepenuhnya. Adapun alasan-alasan yang menyebabkan hal tersebut adalah:
- Sampai tulisan ini dibuat, penulis belum menemukan adanya pengaturan terkait otoritas berkompeten di Indonesia yang mengurus terkait pemberian apostille terkait, sehingga belum ada lembaga yang berwenang mengeluarkan apostille tersebut; dan
- Sampai tulisan ini dibuat, penulis belum menemukan atauran teknis yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, sehingga jajaran hakim, maupun petugas administrasi di bawah Mahkamah Agung menerima kuasa yang dibuat dari luar negeri ini cukup dengan apostille, tanpa legalisir
Dengan dasar tersebut, maka hingga tulisan ini dibuat kuasa yang dibuat di luar negeri dan akan digunakan di pengadilan negeri di Indonesia masih memerlukan legalisir dan hal ini juga terjadi masih banyak terjadi di praktik.
Adanya syarat legalisir pada surat kuasa khusus yang dibuat di luar negeri ini, sejatinya juga bisa dilihat di beberapa putusa, seperti:
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 3038 K/Pdt/1981, tanggal 18 September 1986 yang menyatakan: “keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri selain harus memenuhi persyaratan formil juga harus dilegalisir lebih dahulu oleh KBRI setempat.”
- Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Pti, tanggal 21 Juni 2019 yang menyatakan: Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan dan mencermati Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2018 dari Penggugat prinsipal kepada Kuasa Hukumnya, ternyata tidak ada pengesahan atau dilegalisir oleh KBRI setempat dalam hal ini KBRI Hongkong, sehingga menurut Majelis Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2018 tersebut tidak sah.
Selain adanya kewajiban untuk melakukan legalisir terhadap kuasa yang dibuat di luar negeri sebelum dapat digunakan pada pengadilan di Indonesia, syarat lain adalah adanya kewajiban nazegelen terhadap surat kuasa khusus tersebut. Hal ini dapat dilihat berdasarkan SEMA 7/2012 rumusan kamar perdata, sub kamar perdata umum bagian I huruf f yang menyebutkan: “Surat kuasa yang di buat di Luar Negeri harus dilegalisasi oleh perwakilan RI yaitu Kedutaan atau Konsulat Jenderal di tempat surat kuasa tersebut di buat. (Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09 / A/KP /XII/2006/01 tanggal 28 Desember 2006). Selanjutnya dibubuhi pemateraian kemudian di kantor Pos (naazegelen) (penebalan oleh penulis).” Dengan demikian, berdasarkan SEMA 7/2012 tersebut, terdapat 2 (dua) syarat formil tambahan yang harus ada pada surat kuasa yang dibuat di luar negeri, yaitu:
- Harus dilegalisasi oleh perwakilan RI (Duta/Konsulat); dan
- Nazegelen
Terkait dengan syarat nazegelen pada surat kuasa khusus yang dibuat dari luar negeri ini, banyak orang yang tidak mengetahuinya, bahkan hampir sebagian besar hakim dan staff pengadilan yang tidak mengetahui akan hal ini. Tidak banyak yang tau akan hal ini, karena umumnya nazegelen atau pemeteraian kemudian ini dipahami hanya untuk dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti (Asnawi, 2020). Secara normatif, penggunaan pemeteraian kemudian ini, dapat dilihat di dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai (UU 10/2020), disebutkan bahwa digunakan untuk: “a. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata; dan b. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.”
Terlepas dari tidak banyaknya orang yang mengetahui adanya syarat nazegelen pada surat kuasa khusus yang dibuat dari luar negeri ini, karena umumnya memahami nazegelen digunakan sebagai alat bukti, namun dikarenakan syarat ini telah diatur di dalam SEMA 7/2012, maka berdasarkan asas fiksi hukum, yaitu ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan, maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (presumption iures de iure) (Kadarudin, 2021), sehingga syarat nazegelen tersebut dianggap sudah diketahui oleh orang tersebut. Lebih lanjut, berdasarkan asas hukum ignorantia jurist non excusat yang berarti ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (Candra, 2021), maka meskipun orang tersebut tidak mengetahui adanya syarat nazegelen pada surat kuasa khusus yang dibuat dari luar negeri ini, namun orang tersebut tetap wajib memberikan nazegelen kepada surat kuasa khusus tersebut.
Berdasarkan uraian di atas, maka syarat keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat di luar negeri sejatinya memiliki syarat yang sama dengan surat kuasa khusus secara umum dan ditambah dengan syarat tambahan untuk surat kuasa khusus yang dibuat di luar negeri. Berikut adalah gambar terkait syarat keabasahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri tersebut:
Gambar 2.
Syarat Keabasahan Surat Kuasa Khusus Yang Dibuat Di Luar Negeri

Epilog
Berdasarkan uraian di atas, maka syarat keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat di luar negeri sejatinya memiliki syarat yang sama dengan surat kuasa secara umum (menyebutkan secara jelas dan spesifik kegunaan surat kuasa khusus tersebut [ringkasan dan pokok objek sengketa], menyebutkan secara jelas dan spesifik peran pada tingkat pengadilan tertentu yang akan digunakan, menyebutkan secara jelas kompetensi relatif terkait, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak secara detail) dan ditambah dengan syarat tambahan untuk surat kuasa khusus yang dibuat di luar negeri (Harus dilegalisasi oleh perwakilan RI [Duta/Konsulat] dan nazegelen). Dari syarat-syarat tersebut, adapun syarat yang banyak tidak diketahui adalah terkait kewajiban dilakukannya nazegelen. Banyaknya pihak yang tidak mengetahui syarat tersebut, karena umumnya orang mengira nazegelen dipahami hanya untuk dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti. Terlepas dari diaturnya syarat nazegelen pada surat kuasa khusus yang dibuat dari luar negeri berdasarkan SEMA 7/2012, namun memang hal ini bisa dibilang cukup unik, karena seyogyanya memang nazegelen hanya untuk dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti, akan tetapi seperti pepatah latin, bahwa omnia causa fiunt (semua terjadi pasti karena ada alasan), maka tentunya ada ratio legis dari Mahakamah Agung, sehingga membentuk Surat Edaran yang mewajibkan adanya nazegelen terhadap surat kuasa khusus yang dibuat dari luar negeri tersebut. Agar masyarakat dapat melakukan nazegelen tersebut, seyogyanya Mahkamah Agung memberikan pemahaman terkait ratio legis adanya nazegelen terhadap surat kuasa yang dibuat dari luar negeri tersebut, karena dengan memahami ratio legis tersebut, maka masyrakat tentunya akan memahami urgensinya, sehingga dapat menerapkannya. Hal ini seperti ungkapan Fidelma kepada Eadulf di dalam novel The Dove of Death: A Mystery of Ancient Ireland (Mysteries of Ancient Ireland featuring Sister Fidelma of Cashel) karangan Peter Tremayne, bahwa (Tremayne, 2009): “ Omnia causa fiunt, Eadulf. Everything happens for a reason. But we can only speculate after we have the information to do so. And that is theproblem. We have no information.”
Ditulis Oleh : Xavier Nugraha, S.H.
Daftar Bacaan
Ali, A. (2009). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang Undang (Legisprudence),-Volume I, Pemahaman Awal. Kencana Prenada Media Group.
Apeldoorn, L. J. van. (2019). Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht) (O. Sadino (ed.); Cetakan ke). Balai Pustaka.
Asnawi, M. N. (2020). Pengantar Jurimetri dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Terhadap Hukum. Pranada Media.
Boukala, S. (2016). Rethinking Topos In The Discourse Historical Approach: Endoxon Seeking And Argumentation In Greek Media Discourses On ‘Islamist Terrorism.’ Discourse Studies, 18(3), 249–268.
Candra, M. (2021). Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. Kencana Prenada Media Group.
Fajarwati, M. (2017). Validitas Surat Edaran Mahkamah Agung (sema) Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Jurnal Legislasi Indonesia, 14(2), 145–162.
Garner, B. A. (2014). Black’s Law Dictionary (Tenth Edit). West (Thomson Reuters).
Gumilang, D., Yudianto, O., & Setyorini, E. H. (2019). Legalitas Surat Kuasa Yang Diterbitkan Seorang Buron. Jurnal Hukum Magnum Opus, 2(2), 125. https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2497
Harahap, M. Y. (2017). Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Edisi Kedu). Sinar Grafika.
Hartanto, H. (2019). Tuntutan atas Hak Sangkal Pemberi Kuasa Kepada Penerima Kuasa dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Antara Ancaman dan Pengejawantahan Hak Imunitas Profesi Advokat). Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper, 5(1), 74.
Hollingsworth, A. (2015). “The Beginning of Wisdom is the Definition of Terms” – Socrates. The Breast Journa, 21(2), 119–120.
Kadarudin. (2021). Penelitian Di Bidang Hukum (Sebuah Pemahaman Awal). Formaci.
Ni Made Ayu Sintya Dewi, & Sukranatha, A. A. K. (2017). Syarat Sahnya Surat Kuasa Substitusi Yang Dibuat Di Luar Negeri Dalam Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia. Hukum Universitas Udayana, 1–13.
Putra, P. B. D., Darmadi, A. A. N. Y., & Parwata, I. G. N. (2016). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting). Kerta Wicana, 5(6), 3.
Suslianto. (2019). Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 56 Kuhap Dalam Proses Peradilan Pidana. Jurnal Al-Himayah, 3(1), 127–143.
Svinarky, I. (2019). Bagian Penting yang Perlu Diketahui dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia. Cv Batam Publisher.
Tim Pokja Laporan Tahunan MARI. (2020). Laporan Tahunan 2020 Mahkamah Agung Republik Indonesia Optimalisasi Peradilan Modern Berkelanjutan.
Tremayne, P. (2009). The Dove of Death A Mystery of Ancient Ireland. St. Martin’s Press.